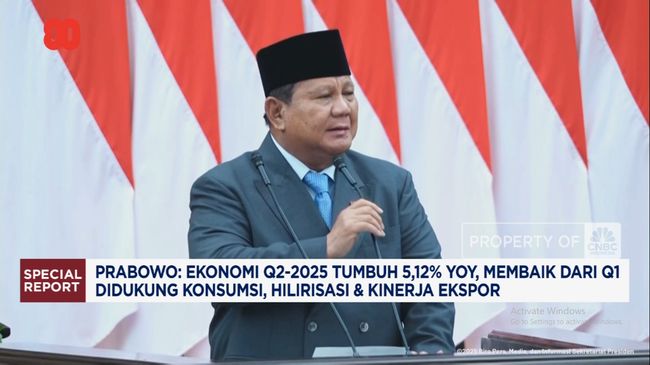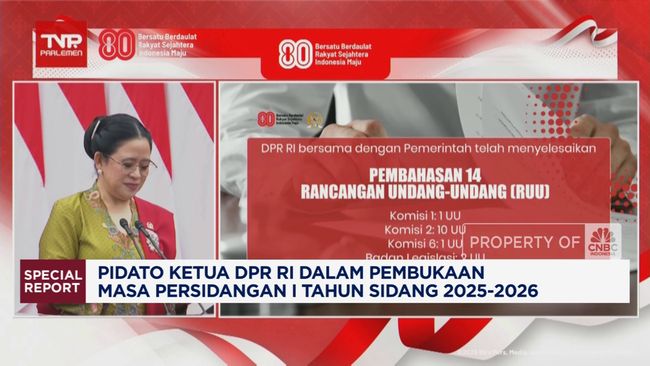Sejarah mengajarkan bahwa pajak bukan sekadar soal pendapatan negara, tetapi urat nadi dan sumber legitimasi kekuasaan.
Kenaikan pajak yang signifikan sering kali lebih dulu memukul ekonomi rakyat kecil. Meningkatnya beban hidup yang tidak diiringi kenaikan pendapatan, menciptakan stress dan ketegangan sosial yang mudah meletup menjadi perlawanan. Dalam konteks ini, kenaikan pajak bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga menyentuh rasa keadilan masyarakat. Ketika rasa keadilan itu dilanggar, stabilitas politik pun ikut terguncang.
Kita bisa menengok pada Revolusi Prancis 1789 yang dipicu oleh sistem pajak yang menindas rakyat miskin. Raja membebani petani dengan pungutan berat, sementara bangsawan menikmati hak istimewa tanpa beban yang sepadan. Ketimpangan ini menimbulkan kemarahan besar yang akhirnya menggulingkan monarki.
Revolusi Amerika juga memiliki akar serupa, meskipun dalam konteks yang berbeda. Slogan “No taxation without representation” (1760) lahir dari penolakan terhadap pajak sewenang-wenang yang tidak disertai hak politik bagi rakyat.
Pengalaman serupa juga terjadi di Nusantara pada masa VOC dan kolonial Belanda. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-19, VOC memberlakukan pajak (contingenten) dan pungutan hasil bumi (verplichte leverantie). Petani dipaksa menyerahkan rempah atau padi dengan harga sepihak, sering jauh di bawah nilai pasar. Beban ini diperparah dengan kerja paksa (herendiensten), yang walaupun bukan pajak uang, tetapi memeras tenaga rakyat demi melayani sang raja (pejabat).
Kebijakan pajak kolonial ini meninggalkan trauma kolektif yang panjang. Pajak bukan dilihat sebagai sarana membangun kesejahteraan, tetapi sebagai instrumen penindasan.
Kesadaran inilah yang kemudian menjadi bagian dari semangat perlawanan nasional awal abad ke-20. Bagi rakyat Indonesia, kedaulatan ekonomi berarti terbebas dari pajak yang menguntungkan segelintir dan memiskinkan banyak pihak. Maka jangan heran, ketika pajak dinaikkan secara ekstrem di masa kini, trauma sejarah itu pun kembali bergaung.
Berbagai peristiwa di atas membuktikan bahwa pajak adalah kontrak sosial, bukan sekadar kewajiban hukum. Jika kontrak tersebut dilanggar, legitimasi kekuasaan akan runtuh. Gerakan protes 13 Agustus 2025 di Pati dapat dibaca dalam bingkai ini.
Rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen jelas memukul sendi ekonomi warga. Bagi petani, pedagang, dan pekerja kecil, kebijakan ini adalah pukulan ganda di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik.
Dari perspektif sosiologis, protes ini bukan hanya soal nominal pajak. Ia adalah ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap abai pada kesejahteraan rakyat. Kesenjangan kekuasaan dan rasa ketidakadilan mempercepat lahirnya solidaritas perlawanan. Dan ketika perlawanan ini menyala, api perubahan sulit untuk dipadamkan.
Kenaikan pajak ekstrem di Pati hanyalah puncak gunung es. Publik telah lama jenuh dengan kebijakan yang mengabaikan nalar dan rasa keadilan. Proyek-proyek mercusuar tanpa manfaat nyata dan regulasi yang menguntungkan segelintir orang menjadi catatan pahit dalam memori kolektif. Korupsi yang merajalela memperdalam luka tersebut. Setiap kasus yang terbongkar adalah pengingat bahwa amanah publik kerap dikhianati.
Uang rakyat yang seharusnya membangun justru menguap di tangan oknum. Hukuman bagi koruptor sering ringan, sementara pelaku tetap menikmati fasilitas mewah. Keadilan terasa timpang—tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ucapan pejabat yang serampangan - bahkan terkesan menantang - semakin memanaskan suasana. Alih-alih menenangkan, ada yang menyalahkan rakyat saat krisis, menertawakan keluhan tentang kemiskinan, bahkan mengancam mengambil alih aset rakyat yang menganggur.
Akumulasi kebijakan yang

 1 day ago
2
1 day ago
2